 Judul buku : Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia
Judul buku : Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia
Penulis : M Kholid Syeirazi
Pengantar : K Tunggul Sirait
Penerbit : Pustaka LP3ES, Jakarta
Cetakan : Pertama, Juli 2009
Tebal : xxi + 328 halaman
Dalam suasana pemilu dan pilpres 2009 yang lalu, diskusi tentang neoliberalisme ekonomi sempat ramai dibicarakan di berbagai media. Sayangnya, masalah tersebut cenderung berkembang sebagai isu politik sesaat dalam konteks yang cukup pragmatis, sehingga substansi masalahnya kurang tersentuh. Salah satu indikasinya, saat ini masalah tersebut kembali redup tergantikan isu lainnya.
Buku yang ditulis oleh M Kholid Syeirazi ini mencoba mengupas satu contoh tentang bagaimana liberalisasi di bidang migas sebagaimana yang tampak dalam UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berimplikasi terhadap masa depan pengembangan industri migas nasional. Kholid juga menelaah konfigurasi ekonomi politik yang melatarbelakangi lahirnya UU tersebut.
Saat dunia belakangan ini dilanda krisis energi, kita semakin sadar betapa minyak memiliki aspek strategis yang sangat signifikan. Kebutuhan akan minyak di semua negara, terutama yang tengah memacu aktivitas ekonomi mereka, sangatlah tinggi. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam minyak terbatas. Karena itu, tak heran jika masalah minyak sering berimbas politis. Keterlibatan Amerika di peta konflik Timur Tengah, misalnya, tak bisa dilepaskan dari kepentingannya untuk memperoleh jaminan suplai minyak.
Membaca uraian yang sangat kaya data di buku yang dikembangkan dari tesis di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI ini, pembaca akan dapat menyimpulkan bahwa UU Migas No 22/2001 bukanlah karya otonom para legislator di DPR dan bukan pula prakarsa otonom negara. Ia lahir dalam suatu konstelasi geopolitik minyak yang menempatkan Amerika sebagai negara yang paling berkepentingan dengan skenario liberalisasi industri minyak di seluruh dunia. Undang-undang tersebut merupakan produk tekanan politis kekuatan ekonomi yang hendak memayungi dan melegalkan jaringan modal dan bisnis mereka di Indonesia.
Ini bisa dirunut dari saat Indonesia terpuruk dalam krisis moneter di penghujung 1997, yang kemudian menempatkan Indonesia tergolek di kursi pasien lembaga kreditor internasional seperti IMF dan World Bank. Mereka itu kemudian menyodorkan resep liberalisasi dan deregulasi sektor keuangan yang di antaranya mewujud dalam bentuk pencabutan subsidi pendidikan, pangan, dan kesehatan. Liberalisasi di bidang energi adalah salah satu poin kesepakatan yang membuka peluang bagi masuknya investor asing di sektor hulu dan hilir migas.
Setelah melalui proses yang cukup panjang, yakni sejak Maret 1999, UU Migas yang baru, yang menggantikan UU No 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (UU Pertamina), disahkan DPR pada 23 Oktober 2001. UU ini menjadikan Pertamina tak lagi berpola usaha yang terintegrasi (hulu dan hilir). Peran ganda Pertamina sebagai regulator sekaligus operator dilucuti. Fungsi regulator ditangani oleh BP Migas dan BPH Migas untuk mengatur kegiatan sektor hulu dan hilir, sedang Pertamina menjadi sekadar salah satu pelaku usaha. Dari sinilah, pemain-pemain asing di bidang migas menemukan pintu masuk yang cukup leluasa untuk bermain di komoditi strategis ini.
Dominasi asing dengan kehadiran UU Migas ini menjadi semakin tampak. Jika dengan UU Pertamina No 8/1971 saja partisipasi Pertamina di sektor migas tidak pernah meraih 10 persen, UU Migas semakin menguatkan dominasi maskapai tambang minyak dunia dalam industri migas nasional.
Catatan dan tinjauan kritis dari beberapa fraksi DPR saat RUU Migas digodok tak mampu mementahkan upaya kekuatan internasional yang bermain di belakang untuk melapangkan jalan liberalisasi migas ini. DPR dihegemoni pemerintah, dan pemerintah berada di bawah dominasi dan tekanan lembaga donor. Demikian pula, upaya sejumlah elemen masyarakat yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung di awal 2003 juga berakhir dengan kecewa.
Salah satu argumen untuk menggusur wewenang Pertamina adalah korupsi yang merajalela. Padahal, penghapusan monopoli Pertamina terbukti tak mengakhiri riwayat korupsi di badan usaha ini. Inefisiensi birokrasi baru serta permainan mafia dan calo minyak hingga kini sulit diatasi. Mekanisme impor dan cengkeraman mafia minyak membuat negara dan rakyat harus menanggung harga BBM yang lebih mahal.
Perspektif yang kuat yang ditonjolkan buku ini adalah bahwa UU Migas telah berimplikasi pada rapuhnya kekuasaan negara untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan energi sehingga komoditas strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ini terjerat dalam mangsa spekulasi para pelaku bisnis dunia. K Tunggul Sirait, pensiunan Guru Besar ITB yang juga mantan anggota Pansus RUU Migas DPR RI, dalam pengantar buku ini menulis bahwa bagian-bagian penting buku ini mengingatkan kita bahwa ada “kain merah-putih yang terkoyak” dalam tata kelola energi nasional karena hadirnya UU Migas tersebut, yang dinilai banyak pihak sangat liberal dan mendurhakai Pasal 33 UUD 1945.
Selain ulasan yang komprehensif dan pemaparan data yang lengkap, buku ini menjadi sangat menarik dan kontekstual untuk dibaca karena ia hendak mengajak kita semua merenungkan soal harga diri, martabat, dan kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa. Menjelang 64 tahun Indonesia merdeka, dan melewati satu abad kebangkitan nasional, bangsa kita nyatanya masih harus bergelut dan berjuang keras untuk meraih kedaulatannya. Pertanyaannya: apakah perjalanan Orde Reformasi saat ini sebenarnya mengarahkan kita semua untuk merebut kedaulatan, otonomi, dan kemandirian kita sebagai bangsa, atau justru membuai kita dalam kepalsuan citra kesejahteraan di bawah bayang kekuasaan aktor-aktor global?
Versi yang sedikit berbeda dengan tulisan ini dimuat di Harian Jawa Pos, 26 Juli 2009.
Selasa, 28 Juli 2009
Jerat Liberalisasi dan Kedaulatan Energi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)









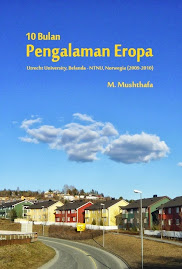




1 komentar:
Wah, jadi ga jelas dong, mana "tuan rumah" dan "mana pengunjung"; jgn2 kita lama2 jadi "stranger in a strange land (IM, 1986), hehehe...
Posting Komentar