Tulisan ini ingin memperkaya perspektif tentang sisi hitam dunia kepenulisan yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi topik yang hangat dibicarakan di rubrik "Di Balik Buku" Jawa Pos. Jika sebelumnya disinggung soal fenomena ghost-writers dan pialang kepengarangan, yang pada satu titik memperlihatkan terkikisnya idealisme dalam dunia kepenulisan, tulisan ini ingin menekankan peranan perangkat teknologi dalam memperlancar berbagai praktik penyelewengan dalam aktivitas kepenulisan tersebut.
Ada satu kasus menarik yang dapat diungkapkan di sini menyangkut hal ini. Seorang rekan saya yang di antaranya mengelola penerbitan buku-buku fiksi remaja, selain buku-buku yang lain, bercerita bahwa ia pernah menerima email komplain dari pembaca yang merasa tertipu karena salah satu buku fiksi remaja yang ia beli sebagian isinya sama dengan buku yang terbit di penerbit lain di kota yang sama, dengan pengarang yang sama, hanya dengan perbedaan tokoh-tokoh dan tempat kejadiannya saja; sementara kalimat hingga titik-komanya pun bahkan persis.
Kasus ini jelas menunjukkan bagaimana perangkat komputer telah benar-benar berperan untuk memudahkan si pelaku dalam menyelewengkan sebuah karya. Tindakan tak bermoral ini tidak dilakukan secara manual dengan sedikit mengotak-atik judul dan segi-segi kebahasaan dalam suatu naskah, tapi cukup diolah dengan bantuan software pengolah kata MS-Word, tekan Ctrl-H, dan seterusnya. Bahkan, duplikasi semacam itu sebenarnya juga bisa dilakukan tidak saja oleh “si penulis asli”, tapi juga oleh orang ketiga, dengan bantuan teknologi scanner. Sebuah buku atau artikel tinggal discan, diambil teksnya, lalu olah di MS-Word (tinggal pilih: apa dengan find-replace, atau copy-paste). Kerja-kerja semacam ini dijamin tak bakalan cukup banyak memeras tenaga—jika dibandingkan dengan aktivitas kepenulisan yang sesungguhnya—dan hanya akan memakan waktu tak lebih dari 1 x 24 jam!
Praktik yang sebelumnya paling lazim dan sederhana dilakukan dengan bantuan kecanggihan komputer adalah mengedit segi-segi kebahasaan naskah, mengganti judul, dan kemudian menjual naskah tersebut ke beberapa penerbit. Rekan saya tersebut di atas juga sempat bertutur bahwa ia pernah dikibuli oleh seorang dosen dari sebuah perguruan tinggi berlabel Islam di sebuah kota yang “berhasil” menjual dan menerbitkan naskahnya ke tiga penerbit di kota itu sekaligus pada waktu yang hampir bersamaan (termasuk ke penerbit yang dikelolanya), dengan beberapa modifikasi yang tidak signifikan. Yang dirugikan jelas penerbit dan pembaca. Pembaca yang kurang cermat bisa jadi akan membeli ketiga buku yang sebenarnya sama itu—dan dengan begitu ia telah menghamburkan uangnya dengan sia-sia. Sementara penerbit, selain akan memperoleh citra kurang baik dari pembaca yang kurang paham duduk soal yang sebenarnya, juga akan membuat market share untuk buku tersebut menjadi berkurang.
Karena itu, tak berlebihan kiranya jika dalam konteks persoalan ini saya ingin menyebut komputer dan perangkat teknologi lainnya itu sebagai “vampir kebudayaan”—meminjam istilah Afrizal Malna dalam salah satu esainya di tahun 1997—, ketika teknologi canggih tersebut dapat juga menjadi semacam penghisap darah kreativitas-sejati manusia dalam aktivitas pengembangan kebudayaan—tanpa harus menafikan segi positif teknologi tersebut—dan mengantarkan pada tindakan-tindakan tak bermoral.
Konon, modifikasi dan pengembangan dari teknologi copy-paste yang relatif sederhana ini telah berkembang pesat, mulai dari mengkopi dan mengedit seadanya beberapa halaman dari sebuah naskah buku terjemahan, untuk kemudian dimasukkan dalam salah satu bagian buku yang diaku sebagai karyanya, hingga dengan modus paling mutakhir yang ditopang dengan fasilitas internet. Belakangan, di lingkungan terbatas, berkembang rumor yang menyatakan bahwa ada sebagian (kecil) penulis di media yang bekerja dengan cara tersebut, dengan memanfaatkan mesin pencari di dunia maya yang memang sangat cerdas itu (semacam “google” atau “altavista”)—dengan bergiga-giga data yang dapat diakses dari seantero dunia, dengan berbagai pilihan bahasa dan tema—bukan untuk diolah sebagai referensi, tetapi dengan lebih banyak comot sana sini, diracik dan digabung-gabungkan, tanpa ada unsur-unsur baru. Dengan kata lain, semacam copy-paste.
Persoalannya sekarang, bagaimana kita menghadapi kejahatan intelektual semacam ini? Bagaimana penerbit dapat mengendus tindak penyelewengan yang memanfaatkan teknologi ini? Terus terang memang sulit rasanya menemukan solusi yang paling mujarab. Menyerahkan tugas penyingkapan kejahatan semacam ini kepada penerbit sebelum menerbitkan suatu naskah jelas terdengar tak masuk akal. Apalagi arus buku-buku baru di pasaran belakangan ini berkembang sangat pesat. Begitu banyak karya terbit, begitu banyak penulis baru muncul; begitu banyak penerbit berdiri dengan lini-lini baru; semakin meluas pula jaringan distribusi penjualan buku ke pelosok nusantara.
Yang paling mungkin dilakukan adalah semacam pemantauan dan sosialisasi tentang modus-modus kejahatan semacam ini, baik kepada para pembaca, peresensi, penerbit, atau siapapun yang peduli, baik melalui forum-forum informal, media massa, atau di forum-forum mailing list. Bila ditemukan, penerbit bersangkutan harus diberi tahu, sehingga untuk selanjutnya, nama “si penjahat”, meski mungkin tak dapat diseret ke pengadilan, harus di-black list dan dibekukan dari daftar jagat kepenulisan. Selain itu, mungkin saja dilakukan jika praktik yang dapat dikategorikan dalam modus plagiarisme ini dimasukkan dalam salah satu klausul surat perjanjian penerbitan, tentu dengan poin yang akan memberatkan pihak penulis. Siapa tahu “si penjahat” akan urung menjual naskahnya justru karena dia kemudian takut ketahuan dan dihukum secara moral oleh masyarakat.
* Tulisan ini pernah dimuat di Harian Jawa Pos, 4 Desember 2005
Kamis, 05 Januari 2006
Vampir Kebudayaan dan Sisi Hitam Dunia Kepenulisan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)









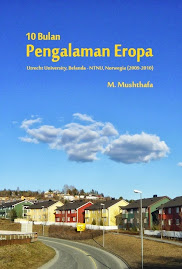




0 komentar:
Posting Komentar